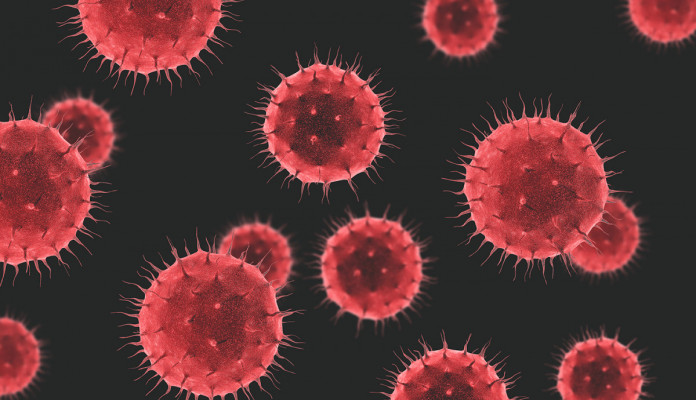Inilah pertanyaan yang sama yang saya ajukan kepada 10 orang yang berbeda di negara yang berlainan:
Mengapa tidak ada virus corona di Indonesia? Percayakah Anda?
“Tidak mungkin tidak ada di Indonesia. Virus ini sudah menyerang seluruh negara di Asia,” jawab seorang teman di Singapura. Ia bukan Robert Lai. Tapi pendapatnya sama dengan Robert.
Tidak satu pun dari 10 orang itu yang percaya kalau virus corona belum masuk Indonesia.
Inilah zaman persepsi –yang fakta kalah dengan persepsi. Dan itulah nasib Indonesia –dipersepsikan seperti itu.
Bahkan ada yang memandang lebih rendah lagi: mungkin peralatan di Indonesia belum memadai untuk bisa mendeteksi virus corona.
Saya hanya tertawa mendengar jawaban yang seperti itu. Apa boleh buat. Reputasi kita memang belum tinggi. Padahal dalam banyak hal kita bisa lebih baik.
Misalnya dalam hal penyakit-penyakit tropik. Pasti dokter Indonesia lebih ahli. Tapi ada saja orang kaya Indonesia yang tetap emosional. Yang mengagungkan dokter Singapura secara membabi buta.
Orang kaya itu terkena demam berdarah. Tinggalnya di Jakarta. Ia segera dibawa ke Singapura karena hanya percaya dokter Singapura.
Saya terlambat tahu itu. Saya tidak sempat menasihatinya. Akhirnya ia meninggal dunia di Singapura.
Masih begitu mudanya –untuk ukuran saya. Ia belum lagi 55 tahun.
Padahal dokter di Indonesia pasti lebih ahli dan berpengalaman menangani demam berdarah. Atau penyakit lain yang sebangsa itu.
Tapi tetap saja dokter kita dipersepsikan kalah.
Teman saya di Beijing menjawab dengan lebih diplomatik. Khas jawaban orang dari sana.
“Saya juga terheran-heran mengapa virus corona tidak menyerang Indonesia,” katanya. “Kalau benar begitu tentu orang Indonesia sangat berbahagia,” tambahnya.
Saya tidak perlu jawaban basa-basi begitu. Saya pun mengejarnya dengan pertanyaan yang lebih tegas: apakah Anda percaya? Akhirnya ia menjawab terus terang: “Sayang sekali saya tidak percaya.”
Ada lagi yang berpendapat bahwa virus corona sudah masuk Indonesia. Hanya saja tidak terdeteksi karena gejalanya hanya mirip flu.
Dan yang terkena ‘flu’ itu ternyata sembuh. Tanpa diketahui mungkin saja itu corona.
Memang banyak rumor yang tidak ilmiah ikut beredar. Misalnya soal suhu udara Indonesia yang panas.
Tapi suhu di Singapura kan juga tidak ada bedanya dengan di Indonesia. Bahkan Australia kini lagi musim panas –toh terkena juga.
Soal rumor tidak makan babi terbantah lebih telak lagi: kan masyarakat Tionghoa Indonesia juga makan babi. Kok juga tidak terkena.
Di Tiongkok sendiri terbukti kian jauh dari Wuhan kian sedikit yang terserang corona. Di Provinsi terjauh, Xinjiang, hanya 71 yang terkena, 11 orang di antaranya sudah sembuh. Hanya satu orang meninggal.
Di Provinsi Ningxia, yang muslimnya juga besar, hanya 70 yang terkena –itu pun yang 33 orang sudah sembuh. Tidak satu pun meninggal.
Demikian juga di Provinsi Qinghai –di antara Ningxia dan Xinjiang– hanya 18 orang terkena tapi yang 13 orang sudah sembuh. Tinggal lima orang yang masih dirawat. Tidak satu pun yang meninggal.
Di provinsi terjauh lainnya, Tibet –yang mayoritas Buddha– hanya satu orang yang terkena corona. Itu pun sudah sembuh.
Yang mengejutkan memang tetap saja Kota Wuhan. Tiga hari yang lalu tiba-tiba saja angka penderita barunya melonjak drastis. Dari biasanya sudah turun ke kisaran 1000, menjadi 14.800.
Hari berikutnya memang turun lagi tapi masih tinggi: 4.800.
Baru kemarin sudah turun lagi menjadi 1.800 orang.
Lonjakan sampai 14.000 lebih itu ternyata bukan karena wabahnya menggila lagi. Mulai hari itu dokter dan perawat dikerahkan terjun ke masyarakat. Dokter dan perawat dari propinsi lain dikerahkan ke Wuhan.
Maka angka penderita barunya tidak lagi hanya yang datang ke klinik. Itu sudah termasuk hasil operasi jemput bola ke tengah masyarakat.
Saya pun tenang. Melonjaknya angka penderita baru akibat gerakan baru jemput bola itu.
Wuhan memang lagi ‘digempur’ habis-habisan. Agar wilayah sumber wabah ini cepat teratasi.
Adakah Indonesia mirip Tibet? Yang penderitanya hanya satu –itu pun kemudian sembuh? (dis)