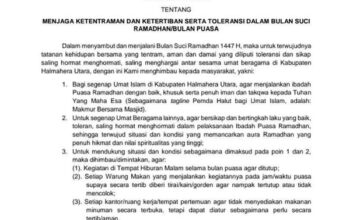Oleh: Renals Y. Talaba, S.IP., M. IP
(Program Stdi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Halmahera)
Dalam konteks sejarah, mengenai Platon dan rezim terbaik, bahwa pada abad ke-5 SM setelah kemenangan Atena atas imperium besar Persia, Atena mengalami kejayaan (sekitar tahun 490-480 SM). Demokrasi yang dipraktekan di Atena, memang berasal dari Atena, lahir di Atena, dengan tokohnya bernama Solon, yang membanggakan Atena sebagai sebuah rezim yang baik dimana rakyatnya begitu bebas dan ikut serta menentukan kebijakan/keptusan politik.
Kemudian rezim ini akan dikokohkan oleh Kleistenes, yang membuat undang-undang, sebagai hukum yang akan menopang dan mengokohkan kesetaraan dan menjadi lebih baik pada era Pericles. Ketika Atena sedang berjaya dan kaya, maka cenderung korup dan pada era 431 SM, muncul perang saudara, yang melemahkan Yunani secara umum dan menghancurkan Atena. Pada tahun 404 SM, Atena akan kalah dan Sparta akan mendudukan rezim boneka, tetapi kemudian Atena akan otonom lagi dan mendudukan rezim demokrasi.
Platon lahir tahun 428 SM dari keluarga bangsawan, dia mengalami sedikit sisa-sisa kejayaan Atena, tetapi dia akan hidup besar, selama perang saudara. Dia akan melihat kehancuran Atena, dia akan melihat demokrasi muncul lagi dan demokrasi yang sama pada tahun 399 SM akan menghukum mati Socrates, gurunya. Setelah kematian Socrates, Platon kemudian mendirikan akademia, jadi ambisi-ambisinya bukan lagi terjun ke dunia politik (lasimnya keluarga bangsawan akan diarahkan untuk masuk ke dunia politik), tetapi Platon memilih jalan lain dan membangun dunia pendidikan. Karena Palton yakin, bahwa dengan pendidikan bisa menciptakan sebuah polis, sebuah negara, dimana orang seperti Socrates, bukan hanya memiliki hak hidup, tetapi juga dihargai secara layak dalam polis itu. Jadi dengan polis dimaksudkan sebagai rumah untuk mewujudkan kebaikan bersama atau rezim terbaik.
Terkait dengan rezim terbaik, Ramlan Surbakti, dalam bukunya memahami ilmu politik, menjelaskan bahwa rezim terbaik ialah keseluruhan tata masyarakat, politik, ekonomi dan sosial budaya yang dianggap terbaik bagi negara bangsa. Dalam tata atau orde masyarakat digambarkan watak manusia, apakah mementingkan diri sendiri (selfish) atau makhluk sosial, tujuan yang hendak dicapai, bagaimana mencapai tujuan dan bagaimana hubungan antara pemerintah dan individu (warga masyarakat).
Berdasarkan asumsi adanya kesejajaran antara cara hidup manusia dan tata masyarakat (jiwa manusia), Platon membedakan rezim menjadi lima tipe, yang pertama Aristokrasi. Tipe ini dikategorikan sebagai rezim terbaik karena yang memerintah adalah seorang raja yang bijaksana (filsuf). Keadilan akan terwujud dalam tipe rezim filsuf sebab rasio manusia yang menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan; seperti sais yang mengendalikan kuda putih dan kuda hitam dari kereta bersayap dalam perumpamaan Platon tentang jiwa manusia. Artinya, dengan menggunakan sistem manusia, rasio, pikiran/akal budi digunakan untuk menimbang, menata cara berpikir, terutama dalam hal menundukan hasrat-hasrat tumos dan epitumos.
Namun sebagus-bagusnya rezim para filsuf berkuasa, ketika sais kereta tidak mampu mengendalikan kuda putih dan kuda hitam (harga diri dan makan, minum seks), maka kereta akan berjalan tidak seimbang. Pada saat itulah maka rezim filsuf raja akan merosot. Setelah resim filsuf raja, akan muncul rezim yang namanya timokrasi (rezim terbaik ke dua), yang diperintah oleh mereka yang menyukai akan kehormatan dan harga diri (prajurit), yang dijiwai dengan semangat.
Rezim demokrasi akan merosot, maka akan muncul resim yang namanya oligarki, dimana dalam oligarki bukan harga diri lagi yang menjadi tujuan, bukan tumos yang dikedepankan, tetapi kekayaan. Dan rezim oligarki ketika berkuasa akan memunculkan kesenjangan luar biasa, pada saat itulah rakyat akan memberontak, maka muncullah kekuasaan rakyat, namanya demokrasi. Dan ketika rakyat berkuasa, semuanya bingung dan ketika semuanya bingung, maka semua rindu tangan yang kuat, dengan tidak lagi mempersoalkan kebebasan, yang penting hidup ini jelas (rezim tirani). Misalnya, mereka yang masih sering membanding-bandingkan rezim orde baru dan rezim reformasi, ada yang masi terpesona dengan rezim Soeharto.
Tirani menjadi ujung dari siklus politik yang diteorikan Platon, artinya Platon memberikan alternatif, tetapi alternatif yang harus dipikirkan, maksudnya rezim tirani belum bersifat finis, dimana siklusnya masi terus berubah dan akan berganti dengan rezim yang lain, apabila dalam pelaksanaannya mengalami kontradiksi dengan akal budi. Sebagus apapun alternatif itu, sejauh ada dalam dunia inderawi, itu akan membusuk, dimana yang ideal itu hanya idea dan hanya idea yang tidak akan berubah, seperti sama, beda, diam, gerak dan ada.
Untuk maksud tersebut, demokrasi telah menjadi pilihan, menjadi konsensus bersama dalam upaya membangun rezim terbaik di Indonesia dan tidak ada lagi yang mempersoalkan, tidak ada yang mempertanyakan secara terbuka, artinya tidak perna terdengar keinginan, ada yang hendak memilih monarki atau diktator dan/atau pemerintahan militer.
Walaupun demokrasi sudah menjadi pilihan dan ditetapkan secara utuh dalam konstitusi, kadang-kadang yang menjadi persoalan atau menjadi bahan perdebatan ialah pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan bernegara, yaitu sistem pemerintahan dan cara mengatur kehidupan bernegara, juga mengenai kekurangan dan kelemahan yang ada, sehingga tidak mencerminkan demokrasi yang benar atau yang sesungguhnya.
Menelusuri sejarah perkembangan demokrasi, tidak ada yang lebih mencengangkan dari sejarah peradaban dunia seperti yang dialami bangsa Yunani kuno pada tahun 600-an SM. Menurut Andrew Gregory dalam Augustinus Setyo Wibowo, ada beberapa alasan yang memungikutinya. Pertama, tumbuhnya budaya demokrasi; kedua, kebebasan beragama (meskipun relatif); berbeda dengan banyak masyarakat tradisional lainnya, di Yunani tidak ada agama yang hirarkhi atau terpusat (misalnya pada figure raja), atau tidak ada agama yang terpusat dengan kelas imam yang khusus. Ini berbeda dengan Babilonia yang memiliki agama terpusat dan masyarakatnya tersusun secara hierarkhis (termasuk dengan kelas imamnya). Masyarakat Yunani lebih memiliki keterbukaan soal agama. Kebebasan ini selanjutnya memberi ruang besar pada perdebatan; ketiga, masyarakatnya cukup kaya sehingga memiliki waktu luang untuk berdiskusi dan berdebat mengenai hal-hal yang tampaknya tak berguna (soal-soal filosofis dan sains).
Sebagai pelaksanaan dari wujud demokrasi Indonesia (demokrasi prosedural), kita telah melaksanakan beberapa kali pemilihan umum pasca reformasi (pemilihan anggota legislatif dan penyelenggara/ eksekutif), namun di negara-negara yang otoriter bahkan yang totaliter sekalipun, diadakan pemilihan umum secara berkala.
Memang banyak kekuarangan dan kelemahan demokrasi yang dipraktekan di negara kita, misalnya dalam hubungannya dengan sistem pemerintahan presidensial dan sistem kepartaian multi partai, yang berimplikasi pada cost politik yang tinggi dalam sirkulasi kekuasaan politik, sehingga kecenderungan terpilihnya kontestan politik dalam pemilu, terbatas pada orang-orang yang memiliki kekayaan. Dengan demikian, setelah terpilih, langkah pertama yang dipikirkan bukan kebaikan bersama, tetapi bagaimana mengembalikan pengeluaran dan mengumpulkan kekayaan untuk kontestasi berikutnya, dengan cara-cara yang bisa benar atau dengan cara-cara yang bisa juga keliru.
Berbicara tata kelembagaan, tentunya negara kita sudah banyak belajar soal praktek demokrasi dari berbagai negara, baik melalui teks-teks sejarah Yunani Kuno maupun secara langsung dari negara-negara yang punya kelebihan dan kelemahan menjalankan sistem politik demokrasi. Sangat absurd, jika mengevaluasi pelaksanaan demokrasi di Indonesia dan terus mengatakan, penyebab merosotnya demokrasi ke oligarki yang diperlihatkan saat ini karena tata politik dan tata pemerintahannya yang belum memadai.
Pertanyaannya, apakah tata kelembagaan dan pembuat kebijakan bisa dimaknai secara dikotomis? Itu sama halnya dengan mengatakan, ketika manusia masih bernapas, manusia masih hidup, jiwa perna keluar dari tubuh dan melakukan pekerjaannya sendiri dan jiwa kemudian menuduh tubuh sebagai pihak yang bersalah, karena hanya berdiam diri.
Merosotnya demokrasi dalam pelaksanaannya yang memunculkan fenomena oligarki saat ini, karena jiwa (sais) pembuat kebijakan belum optimal. Argumentasinya sederhana, evaluasi terhadap demokrasi sudah berulang kali dilakukan, dengan pokok persoalan yang muncul selalu sama bertahun-tahun yakni pada aspek disain tata kelembagaan, namun nyatanya negara tidak konsisten terhadap komitmen perbaikan tata kelola kelembagaan tersebut, padahal negara paham betul implikasinya terhadap perilaku politik pembuat kebijakan dan perilaku warga masyarakat.
Jika demokrasi dianalogikan dengan sebuah pohon pengetahuan untuk memahami keutamaan tata lembaga pemerintah dan pembuat kebijakan, dimana akar pohonnya dianalogikan dengan metafisika, batangnya adalah fisika, cabang-cabangnya adalah bidang-bidang ilmu yang lain dan daunnya adalah lembaga negara (supra struktur), maka sinar matahari adalah akal budi. Maka dalam demokrasi akarnya adalah rakyat, batangnya adalah pembuat kebijakan, sebagai penyalur bahan makanan, air dan mineral-mineral yang diserap oleh akar pohon dari dalam tanah.
Seperti batang pohon-fisika, dengan hukum-hukum mekanika (ada gaya dan gerak), maka pembuat kebijakan harus berfungsi seperti ilmu fisika, menjadi perantara yang menggerakan aspirasi rakyat dan cabangnya (bidang ilmu yang bermacam-macam) adalah birokrasi yang membantu menopang daun pohon tumbuhan untuk proses fotosintesis. Seperti daun tumbuhan untuk proses fotosintesis, maka lembaga-lembaga negara, harus berfungsi mengolah aspirasi rakyat yang ditopang oleh cahaya akal budi, untuk menjadikannya semacam nutrisi, memenuhi tuntutan kebutuhan kelangsungan hidup demokrasi.
Dengan demikian, maka prinsip logis demokrasi dapat dijelaskan seperti berikut, rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, memiliki kekuasaan sekuler yang bersifat abadi, karena menjadi bawaan sepanjang hidup, sedangkan pembuat kebijakan kekuasaannya hanya sementara, berlaku lima tahun karena hanya diminta semnatara dari rakya, dengan perjanjanjian kehendak rakyat itu harus diatur dalam konstitusi untuk menegakan kesetaraan dan mewujudkan keadilan. Karena diminta dari rakyat, posisi rakyat dalam kekuasaan demokrasi lebih tinggi dari pada pembuat kebijakan, maka pembuat kebijakan harus mampu menundukan hasrat-hasrat jiwanya (tumos dan epitumos) dibawah saisnya, namun faktanya bertolak belakang, dimana praktek demokrasi sepertinya mengikuti watak oligarki, yang memainkan penanda kebenaran, yang tidak jelas dan tidak terpilah.
Untuk memahami watak manusia dan orde masyarakat, tulisan ini mengangkat konsepsi (filsafat standar) Platon tentang jiwa manusia, dalam memahami pelaksanaan demokrasi dengan tidak membuat dikotomi antara tata lembaga pemerintah dan pembuat kebijakan, karena itu sama halnya dengan manusia yang membuat kesalahan, tidak mungkin hanya menyalahkan jiwa ataupun menyalahkan badan, tetapi perlu memahaminya secara utuh, bahwa tata lembaga negara seperti jiwa manusia dan pembuat kebijakan adalah badannya, yang bekerja menurut petujuk dan arahan yang berasal dari jiwa.
Dalam makalanya Augustinus Setyo Wibowo, tentang filsafaat keutamaan, mengenai jiwa manusia, Platon memakai perumpamaan, menjelaskan jiwa manusia, seperti kereta bersayap, ada saisnya yang mengendalikan dua kuda (putih dan hitam). Kuda putih adalah tumos (harga diri), yang secara umum disebut afektifitas, sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan rasio. Sedangkan kuda hitam yakni hasrat mencari kenikmatan-kenikmatan (epitumia). Jadi dari interaksi ketiga itu, Platon menyebut jiwa adalah gerak autokineton, yakni gerak yang menggerakan dirinya sendiri dan autokineton akan tampak dalam manifestasi dinamika dari ketiganya, dimana rasio sebagai prinsip nomor satu, yang berikutnya adalah tumos (harga diri, dibagian dada) dan epitumos (makan, minum dan melanjutkan keturunan/dari perut ke bawah).
Platon kemudian menyebutkan, bahwa dalam diri manusia terdapat tiga jenis makhluk, ini sekaligus menjelaskan pembagian kelas dalam masyarakat, yang pertama, manusia kecil, yakni rasio; kedua, singa yakni harga diri dan ketiga adalah monster berkepala banyak, yakni hasrat-hasrat jiwa seperti keinginan, nafsu-nafsu (makan, minum, dan melanjutkan keturunan), yang tidak ada habis-habisnya. Seperti monster, satu kepalanya di potong, muncul kepala monster yang lain. Menurt Platon, manusia kecil, filsuf sebagai penguasa (akal budi); dan singa (harga diri) adalah kelas masyarakat (prajurit) yang bekerja memelihara tata masyarakat (dengan semangat); monster berkepala banyak, yakni pedagang yang bekerja mencari uang sebanyak-banyaknya (nafsu).
Dengan munculnya fenomena demokrasi yang tampak merosot di Indonesia, menunjukan bahwa hasrat-hasrat, nafsu-nafsu dalam pemenuhan kebutuhan manusia belum ditundukan dan diterangi oleh reason (akal budi), dan jaman ini seolah mendukung argumentasi itu, bahwa tindakan apapun bisa dilakukan untuk pemenuhan hasrat-hasrat, nafsu-nafsu yang menghilangkan logos. Sederhananya, ketika kebutuhan hidupnya secara keliru dihasrati manusia, seperti seseorang menghasrati sebuah HP yang mahal, dimana kondisi ekonominya belum memungkinkan untuk itu, namun karena sudah terlanjur menghasrati HP android yang mahal, maka dia sudah menipu dirinya sendiri karena telah menabur benih-benih korupsi, menabur benih-benih kejahatan. Disinilah, logos dinihilkan, logos dievakuasi, logos dilhilangkan, semua sama benarnya, semua sama salahnya, segala sesuatu tidak ada maknanya pada jaman kontemporer ini.
Lalu muncul pertanyaan, apakah melakukan korupsi itu sebuah kejahatan? Platon mengatakan tidak. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh seseorang itu bukan kejahatan, tetapi itu persoalan ketidak tahuan. Misalnya, pembuat kebijakan melakukan korupsi uang negara, tindakannya itu benar karena tujuannya untuk membahagiakan keluarganya, dirinya sendiri dan hal itu dilakukannya karena yang bersangkutan tidak mengetahui. Manusia seringkali tidak sadar menjerumuskan dirinya terhadap hal-hal yang beresiko, karena ia tidak tahu apa yang ia perbuat. Setelah terjebak dalam suatu situasi yang mengekang kebebasannya (karena menentang hukum kodrat dan hukum positif), maka dari kegelapan itu, lahir pengetahuannya dan menyadari bahwa ia sedang dikontrol oleh lingkungan sosial yang lebih besar dan dikontrol oleh kekuasaan yang adikodrati serta sedang diuji oleh pengetahuan sosial yang lebih luas dari pengetahuannya sendiri. Maka lahirlah kemudian bayi pengetahuan dari rahim kesadarannya karena ia mengalaminya sendiri.
Kekacauan watak manusia dan orde masyarakat ini perna ditanggapi Fransesco Trapatoni, seorang ahli Helenis, dari Universitas negeri di Milan-Italia, yang menggambarkan kekacauan jaman ini seperti kekacauan jaman yang perna dibawa oleh kaum sofis di Yunani Kuno. Ia kemudian mengatakan, di jaman kontemporer saat ini kita berhadapan dengan berbagai macam ide yang disebutnya sebagai kebangkitan kaum sofis. Terkait dengan kaum sofis, yakni kelompok orang-orang yang menihilkan logos, mereka hadir pada saat puncak kejayaan dan kekayaan Atena yang melimpah dan pada saat demokrasi menjadi mantap. Karena sering mengatur dan memfasilitasi orang-orang yang berdebat, kaum sofis sering disebut fasilitator demokrasi, mereka mendapatkan pangsa pasar yang membuthkan kemampuan untuk berbicara (rezim kata-kata).
Sofisme disebut Platon sebagai orang-orang yang haus kekuasan, haus uang. Sofisme bukan lagi buruk, bukan hanya sesat, tetapi mereka bermaksud untuk menipu. Platon menjuluki mereka sebagai pemikir-pemikir yang amoral, yang tidak lagi memikirkan soal baik-buruk, soal moralitas, yang penting memenangkan argument dalam meyakinkan masyarakat.
Jadi, soal demokrasi bukan idenya yang salah, tetapi rasio manusianya yang belum lengkap dalam menjalankan demokrasi, dimana tumos dan epitumosnya belum diterangi oleh akal budi, yang membuat demokrasi merosot menjadi oligarki. Contoh kekeliruan manusia, pada suatu saat menafsirkan kebaikan Tuhan dan pada saat yang lain manusia menganggap bahwa Tuhan itu jahat, apakah Tuhan yang disalahkan? Tentunya tidak. Tuhan tidak bisa disalahkan, yang salah adalah cara berpikirnya manusia yang tidak benar tentang Tuhan, yang perlu diperbaiki.
Socrates dan Platon tidak menolak harga diri dan hasrat makan, minum dan melanjutkan keturunan, hal itu tidak dihilangkan dari filsafatnya, namun pertanyaan Socrates dan Platon adalah soal hal-hal menata jiwa secara harmonis. Manusia membutuhkan pemikiran/pengetahuan untuk menimbang, untuk menata cara berpikir terutama dalam hal menundukan hasrat akan harga diri, makan, minum dan melanjutkan keturunan, yang mesti diterangi oleh rasio, hukum moral dan hukum positif, termasuk dalam hal membangun budaya demokrasi untuk terciptanya tata masyarakat, politik, ekonomi, sosial budaya yang dianggap terbaik bagi bangsanya.
Namun jaman ini terus menunjukan kegilaannya, ikut gila tidak tahan, tidak ikut gila tidak mendapat apa-apa. Hal ini terjadi karena setelah abad 19, teori-teori yang percaya pada universalisme, hak asasi manusia, hal-hal yang objektif, etika normatif, sistem hukum yang baik, yang masuk akal, yang disepakati bersama, menjadi kacau. Seperti filsafatnya Deridda tentang post modernisme, dicirikan dengan segala sesuatu yang campur aduk, tidak ada makna di situ, tidak ada kebenaran di situ, semuanya hanyalah permainan penanda, yang tidak merujuk pada makna apapun, semuanya hanya main-main.
Lalu masyarakat menjadi bingung, sampai sebingung-bingungnya mencoba memahami fenomena demokrasi Indonesia hingga memilih sikap hidup berapatea, lalu kita yang terus berpikir mengikuti sejarah yang terus berjalan, berpikir tentang orde masyarakat dan watak manusia setelah jaman modern (post modern), dan melalui peristiwa ambruknya bangunan kembar WTC, pusat perdagangan di AS tahun 2001, kita sedikit menemukan, ternyata kondisi jaman ini bahwa semua peristiwa yang terjadi hanyalah permainan dari satu peristiwa ke peristiwa lainnya, di sana tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah dan anda tidak berhak mengatakan apapun tentang itu, karena hal itu merujuk dari satu peristiwa ke peristiwa lainnya, yang tak habis-habisnya dengan resiko peristiwa itu seolah-olah tidak ada dan berbagai peristiwa yang terjadi menjadi hilang maknanya (konstruksivisme modern rezim kata-kata)****