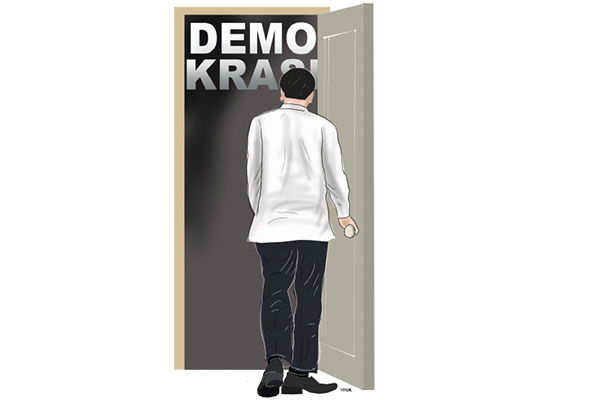Oleh: IGK Manila
Gubernur Akademi Bela Negara (ABN)
SEPANJANG hari-hari bersejarah di pekan ini, sejak pelantikan presiden dan wakil presiden pada Minggu (20/10) sampai dengan pemilihan dan pelantikan para menteri, saya mengikuti dari jauh.
Sejak minggu lalu, saya mendampingi tim wushu Indonesia mengikuti Kejuaraan Dunia Wushu 2019 yang berlangsung di Shanghai, 19-23 Oktober 2019.
Setelah bertahun-tahun terlibat dalam politik praktis dan memimpin penyelenggaraan pendidikan politik di Akademi Bela Negara (ABN) Partai NasDem sejak 2017, saya amat gembira. Dari Shanghai, saya tengah menjalankan tugas negara mendampingi para duta olahraga bangsa, saya melihat arah baru politik Indonesia.
Bisa jadi ada bias militeristik dalam pandangan saya. Akan tetapi, itu ialah hal wajar karena latar belakang karier dan bahkan bisa menjadi satu variasi perspektif yang bermanfaat.
Pilihan politik akomodatif Presiden Jokowi terlihat sebagai jalan tengah. Beliau berusaha mencari jalan keluar di antara dua pilihan ekstrem, yaitu berpolitik dalam skema demokrasi liberal sepenuhnya atau memilih demokrasi yang lebih sesuai dengan realitas kekinian dan kultural Indonesia.
Dalam skema demokrasi liberal, oposisi dipandang sebagai hal mutlak demi adanya mekanisme saling kontrol. Oposisi tidak saja berfungsi sebagai mekanisme kontrol demi keseimbangan, tetapi juga sebagai lawan berdialektika yang memungkinkan terlahirnya konsep-konsep yang lebih baik bagi penyelenggaraan negara.
Bagi sebagian kalangan, konsep berdemokrasi seperti itu bisa disebut sebagai utopis, terutama karena terdapat asumsi atau bahkan prasyarat tentang kedewasaan berdemokrasi. Para politikus dan para pendukungnya diandaikan ialah warga negara yang matang (civilians), yang mampu berpolitik bukan hanya karena mengejar kepentingan sendiri atau kelompok. Namun setelah berpikir, bersikap, dan bertindak karena faktor citizenship, berdemokrasi pada akhirnya ialah demi keutuhan bangsa dan negara.
Politik Akomodatif
Di masa demokrasi terpimpin Orde Lama, di zaman pemerintahan Presiden Soekarno, demokrasi yang disebut langsung, jujur, dan adil pernah terjadi pada 1955. Tingkat keterwakilan partai dan golongan dinilai baik dan intervensi dalam berbagai bentuknya dipandang rendah. Dunia internasional melihat peristiwa ini sebagai hal yang mengagumkan.
Akan tetapi, kita tahu Presiden Soekarno di kemudian hari bereksperimen lain. Tidak sabar dengan kasak-kusuk dan kisruh politik parlementer yang berkepanjangan, beliau memilih menjalankan demokrasi terpimpin. Kekuatan dibuat memusat di tangan satu orang yang dikelilingi representasi partai dan golongan, yang dipandang revolusioner. Puncaknya pada 1965-1966, ekperimen ini gagal.
Sampai taraf tertentu, kita bisa melihat Presiden Soekarno bereksperimentasi dengan politik yang mencoba merangkul semua golongan dalam konsepsi nasionalisme-agama-komunisme (Nasakom). Akomodasi diniatkan untuk menyelesaikan kisruh politik dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang bisa tampil di dunia internasional.
Setelah Orde Lama runtuh, datanglah apa yang diistilahkan sebagai Orde Baru (1966-1998). Sebagai tentara, saya terlibat langsung dalam upaya membangun persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai demokrasi. Namun dilakukan dengan cara-cara yang militeristik, sesuai latar belakang Presiden Soeharto.
Sebagai warga negara, saya melihat apa yang dilakukan pemerintahan Orde Baru juga berbentuk politik akomodatif. Presiden Soeharto dengan berbagai cara berusaha merangkul dan memfasilitasi keragaman latar belakang kultural dan politik masyarakat Indonesia dengan cara menyeragamkan tafsir atas demokrasi Pancasila berdasar pada UUD 1945. Jargon utamanya, kita tahu, ialah pembangunan.
Parpol dipadatkan menjadi tiga saja, yaitu PPP, Golkar, dan PDI. Partai-partai Islam tergabung dalam PPP serta partai-partai nasionalis dan agama non-Islam tergabung dalam PDI. Golkar, gabungan organisasi kemasyarakat yang berdiri sendiri secara politik, kemudian menjadi kendaraan politik Presiden Soeharto sampai Pemilu 1997.
Sampai 1980-an, Indonesia bertumbuh dalam berbagai aspek dan menjadi negara yang disegani dunia. Akan tetapi, desakan publik untuk berdemokrasi secara terbuka dan adil bagi semua masyarakat, terutama karena oligarki yang telah menjadi benalu kehidupan berbangsa dan bernegara, menumbangkan Orde Baru.
Sejak 1998, Indonesia hidup dalam Orde Reformasi. Demokrasi yang sebelumnya bisa dikatakan terpimpin berubah menjadi sangat liberal. Partai tumbuh seperti jamur dan pemilihan dilaksanakan secara langsung. Bahkan kini, dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah, kepala daerah (bupati, wali kota, dan gubernur) juga dipilih langsung serta melahirkan raja-raja kecil yang mengganggu pembangunan.
Hal yang tak terhindarkan dalam demokrasi seperti ini ialah fragmentasi masyarakat yang mudah menajam. Contoh terbaru, Pemilu Serentak 2019 yang membelah masyarakat atas dasar agama dan suku bangsa. Bahkan, yang amat menyedihkan ialah bagaimana demokrasi telah menjadi pintu masuk radikalisme yang pada titik ekstrem bisa menjadi terorisme.
Lebih Optimistis
Apa yang dilakukan Presiden Jokowi bisa jadi terlihat sebagai akomodasi reaksioner atas fenomena fragmentasi sosial ini. Secara historis, jika melihat upaya dua presiden terlama RI dalam eksperimentasi demokrasi terpimpin, Presiden Jokowi bisa jadi juga dilihat terjebak dalam kegalauan atas fenomena politik yang fragmentatif.
Akan tetapi, saya melihatnya dengan cara lebih optimistis. Ada situasi berbeda dalam konteks kini Presiden Jokowi bersikap dan bertindak serta bagaimana akomodasi politik dilakukan. Pertama, kini tengah terjadi apa yang disebut sebagai demokrasi yang semakin langsung.
Presiden Jokowi menjadi pemenang pemilu karena dipilih langsung secara terbuka melalui cara-cara yang legitimate di mata publik. Demikian juga terkait dengan akuntabilitas pemerintahannya, demokrasi langsung telah memungkinkan kontrol yang lebih besar dari masyarakat sipil secara legal formal meskipun efektivitas kontrol ini juga banyak dipertanyakan.
Kedua, cara-cara yang ditempuh Presiden Jokowi sejauh ini juga telah disesuaikan sedemikian rupa. Dalam rangkaian seleksi para calon menteri, sebagai contoh, beliau menguji reaksi pasar dan publik secara luas serta sejauh ini juga respons yang didapat positif.
Cara-cara yang dilakukan juga berbasis akomodasi kultural, terutama dengan asumsi bahwa situasi kultural masyarakat Indonesia lebih berorientasi harmoni. Gejolak sosial menjelang, di saat dan sesudah pemilu dipandang sebagai gejala yang mencemaskan dan mengganggu harmoni. Dengan merangkul partai dan tokoh-tokoh yang berseberangan di masa pemilu diajak untuk berkontribusi, Presiden Jokowi terlihat ingin mengapitalisasi konsep gotong royong.
Sebagai penutup, kecemasan berbagai pihak akan ketiadaan pengontrol dan penyeimbang yang kuat tentu juga tidak bisa diabaikan. Selain kontrol civil society, perlu kesadaran kenegarawanan yang kuat dari para anggota legislatif, meskipun berasal dari partai koalisi pemerintah atau partai yang sama dengan para menteri sebagai eksekutif.
Mudah-mudahan apa yang dilakukan Presiden Jokowi bukan hanya sekadar menjadi eksperimentasi politik yang efektif, melainkan lebih jauh juga menjadi wahana bagi pendidikan politik bagi seluruh warga negara. Hal itu hanya menjadi nyata jika anggukan setuju dan apatisme dikalahkan partisipasi aktif yang tiada henti.(*)
Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/267477-jokowi-dan-pendidikan-politik